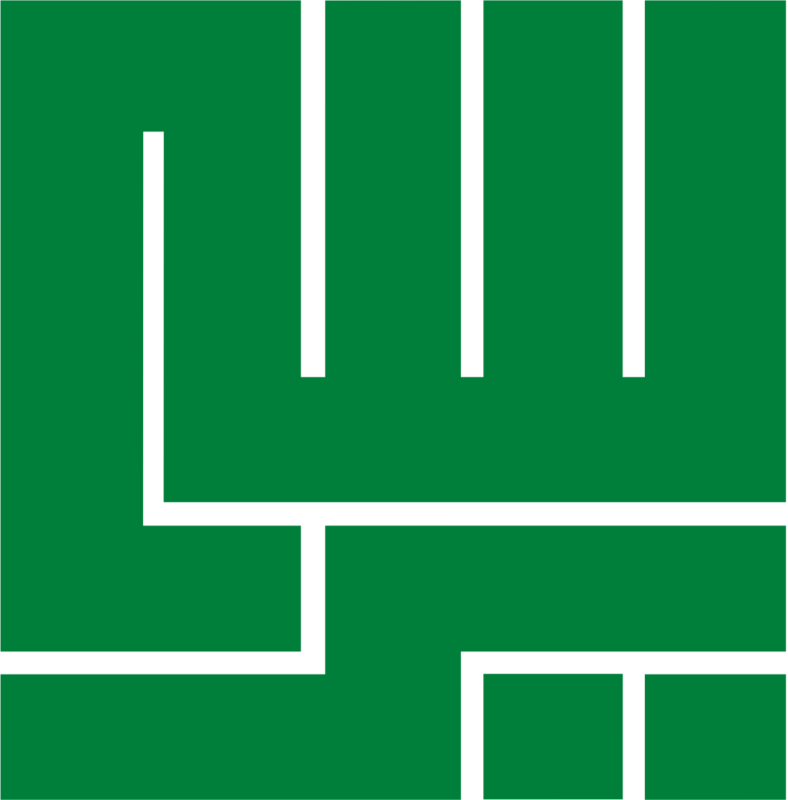Pendidikan tinggi di Indonesia sedang menghadapi ketimpangan serius yang mengancam keberlangsungan ekosistem akademik. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) semakin kesulitan menarik mahasiswa baru, sementara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agresif menjaring calon mahasiswa melalui berbagai jalur pendaftaran dan program studi (prodi) baru yang sering kali belum teruji. Jalur pendaftaran PTN, yang berfungsi seperti “pukat harimau” yang menjaring semua segmen calon mahasiswa—dari yang berprestasi hingga yang memiliki kemampuan finansial tinggi—telah menyisakan sedikit peluang bagi PTS, yang ibarat “nelayan tradisional” berjuang untuk bertahan.
Fenomena ini tidak hanya mengancam kelangsungan PTS, tetapi juga stabilitas sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) mengumumkan kebijakan pembatasan penerimaan mahasiswa PTN hingga Juli 2025 sebagai respons terhadap krisis ini. Namun, kebijakan ini bersifat reaktif, dangkal, dan jauh dari solusi ideal. Artikel ini menganalisis akar masalah, dampaknya, dan mengusulkan solusi, dengan penekanan pada regulasi untuk membatasi ekspansi PTN agar ekosistem pendidikan tinggi kembali seimbang.
Fenomena “Pukat Harimau” PTN dan Krisis Mahasiswa PTS
Data dari Kemendiktisaintek pada 2024 menunjukkan bahwa sekitar 30% PTS hanya mampu merekrut kurang dari 50% kuota mahasiswa baru. Di daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, beberapa PTS kecil terpaksa tutup karena tidak mampu menutup biaya operasional. Sebaliknya, PTN seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) terus meningkatkan daya tampung melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan jalur mandiri. Unesa, misalnya, menerima hingga 14.000 mahasiswa baru per tahun, sementara PTS lokal seperti Universitas Wijaya Kusuma atau Universitas Muhammadiyah Surabaya hanya mendapat ratusan pendaftar.Jalur pendaftaran PTN yang beragam—SNBP untuk siswa berprestasi, SNBT untuk seleksi berbasis tes, dan jalur mandiri untuk mereka yang bersedia membayar biaya masuk tinggi—berfungsi seperti “pukat harimau” yang menjaring semua segmen calon mahasiswa. Jalur mandiri, khususnya, menjadi sorotan karena memungkinkan PTN menarik mahasiswa dari kelas menengah atas, yang seharusnya menjadi pasar utama PTS.
Di beberapa PTN ternama, jalur mandiri bahkan menyumbang hingga 40% dari total mahasiswa baru, dengan biaya masuk yang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, PTN agresif membuka prodi baru, seperti kecerdasan buatan, data sains, hingga prodi kontroversial seperti “teknologi influencer,” yang sering kali minim kajian pasar atau landasan akademik yang kuat. Akibatnya, PTS kehilangan daya saing, terutama di daerah di mana PTN mendominasi.Kebijakan baru Mendiktisaintek untuk membatasi penerimaan mahasiswa PTN hingga Juli 2025 bertujuan untuk mengurangi dominasi PTN dan memberikan ruang bagi PTS untuk menarik mahasiswa. Namun, kebijakan ini bersifat sementara dan tidak disertai dengan langkah pendukung yang memadai, sehingga tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam ekosistem pendidikan tinggi.Akar
Masalah
Kebijakan Ekspansif PTN dan Ketimpangan Dukungan
Krisis ini berpangkal pada beberapa faktor utama, seperti:
Pertama, persepsi masyarakat yang menganggap PTN lebih prestisius dan terjangkau menjadi pendorong utama. Biaya kuliah di PTN, meskipun melalui jalur mandiri, sering kali lebih rendah dibandingkan PTS, terutama dengan adanya skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disubsidi.
Kedua, PTN memiliki akses lebih besar ke sumber daya, seperti dana penelitian, fasilitas modern, dan jaringan alumni yang kuat, yang membuatnya lebih menarik.
Ketiga, kebijakan PTN yang memperluas jalur masuk dan prodi baru menciptakan persaingan tidak sehat. Jalur mandiri, misalnya, tidak memiliki batasan kuota yang jelas, memungkinkan PTN “menyedot” calon mahasiswa yang seharusnya menjadi target PTS.
Kebijakan pemerintah juga memperparah ketimpangan. PTN menerima alokasi anggaran besar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur dan penelitian, sementara PTS hanya mendapatkan bantuan terbatas, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Regulasi yang longgar terhadap pembukaan prodi baru di PTN, tanpa evaluasi ketat terhadap relevansi atau kualitas, juga menjadi masalah. Sebaliknya, PTS dihadapkan pada regulasi ketat, seperti moratorium pembukaan PTS baru sejak 2018, yang membatasi masuknya pemain baru yang potensial. Banyak PTS juga gagal bersaing karena kualitas yang tidak merata, kurangnya inovasi, atau minimnya kemitraan dengan industri.
Kebijakan pembatasan penerimaan PTN hingga Juli 2025 tidak menangani akar masalah ini. Kebijakan ini bersifat reaktif, hanya berfokus pada pengurangan kuota PTN tanpa mengatasi ketimpangan sumber daya, persepsi masyarakat, atau regulasi yang tidak seimbang. Selain itu, sifatnya yang sementara menunjukkan kurangnya komitmen untuk reformasi jangka panjang.
Dampak: Ancaman terhadap Keberagaman dan KeberlanjutanKetimpangan ini memiliki konsekuensi serius.
Pertama, penutupan PTS, terutama di daerah terpencil seperti Kalimantan atau Sulawesi, mengurangi akses pendidikan tinggi bagi masyarakat lokal, yang sering mengandalkan PTS sebagai pilihan terjangkau.
Kedua, overcrowding di PTN berpotensi menurunkan kualitas pendidikan karena rasio dosen-mahasiswa yang tidak ideal dan fasilitas yang terbatas. Ketiga, prodi baru di PTN yang belum teruji berisiko menghasilkan lulusan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja, memperburuk angka pengangguran terdidik, yang pada 2024 mencapai 7,86% menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
Lebih jauh, dominasi PTN mengancam keberagaman ekosistem pendidikan tinggi. PTS sering menawarkan fleksibilitas kurikulum, seperti program vokasional atau kewirausahaan, yang tidak selalu dimiliki PTN. Jika PTS terus melemah, Indonesia berisiko kehilangan inovasi pendidikan dari sektor swasta, yang selama ini menjadi pelengkap penting bagi PTN. Ketimpangan ini juga dapat memperlebar kesenjangan sosial, karena PTN cenderung menarik mahasiswa dari kelas menengah atas, sementara PTS sering menjadi pilihan bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.
Kritik terhadap Kebijakan Pembatasan Penerimaan PTN
Kebijakan Mendiktisaintek untuk membatasi penerimaan mahasiswa PTN hingga Juli 2025 adalah respons yang reaktif, dangkal, dan jauh dari solusi ideal.
Pertama, kebijakan ini bersifat reaktif karena hanya menanggapi gejala krisis pendaftaran PTS tanpa menyelesaikan akar masalah, seperti ekspansi jalur mandiri PTN atau pembukaan prodi baru yang tidak relevan.
Kedua, kebijakan ini dangkal karena tidak disertai dengan langkah pendukung, seperti peningkatan dana untuk PTS, evaluasi ketat terhadap prodi PTN, atau kampanye untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap PTS. Ketiga, kebijakan ini jauh dari ideal karena hanya bersifat sementara hingga Juli 2025, tanpa jaminan reformasi berkelanjutan. Ada pula risiko dampak negatif, seperti berkurangnya akses pendidikan tinggi jika PTS tidak mampu menyerap mahasiswa yang dialihkan akibat keterbatasan sumber daya atau daya tarik.
Solusi: Regulasi Ketat dan Dukungan untuk KeseimbanganUntuk mengatasi krisis ini dan mengembalikan keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi, diperlukan kebijakan yang strategis dan terarah. Berikut solusi yang diusulkan, dengan penyesuaian untuk mengatasi kelemahan kebijakan pembatasan PTN:
Regulasi Pembatasan Jalur Pendaftaran PTN yang Diperkuat:
Pemerintah harus memperpanjang dan memperbaiki kebijakan pembatasan penerimaan PTN di luar Juli 2025, dengan menetapkan kuota maksimal untuk jalur mandiri (misalnya 20-30% dari total daya tampung) dan memastikan seleksi berbasis meritokrasi, bukan hanya kemampuan finansial. Regulasi ini akan mencegah PTN bertindak seperti “pukat harimau” yang menjaring semua segmen calon mahasiswa, sehingga menyisakan peluang bagi PTS untuk bersaing. Pemerintah juga dapat mewajibkan PTN untuk memprioritaskan jalur SNBP dan SNBT, yang lebih adil dan transparan, serta membatasi biaya masuk jalur mandiri agar tidak terlalu kompetitif dibandingkan PTS.
Evaluasi Ketat Prodi Baru
Kemendiktisaintek harus menerapkan evaluasi ketat terhadap pembukaan prodi baru di PTN, dengan melibatkan badan akreditasi independen untuk menilai relevansi pasar, kualitas akademik, dan dampak terhadap ekosistem pendidikan tinggi. Prodi yang tidak memenuhi standar, seperti yang berbasis tren sesaat tanpa landasan akademik kuat, harus ditunda atau dibatalkan.
Dukungan Finansial untuk PTS
Pemerintah perlu meningkatkan bantuan untuk PTS melalui skema dana abadi pendidikan tinggi, insentif pajak untuk investasi pada riset dan fasilitas, atau subsidi untuk PTS di daerah tertinggal. Program pelatihan dosen dan modernisasi infrastruktur juga harus diperluas ke PTS, bukan hanya PTN. Misalnya, pemerintah dapat mengalokasikan dana khusus untuk PTS dengan akreditasi baik yang menawarkan prodi strategis, seperti teknologi hijau, kesehatan digital, atau ekonomi digital.
Peningkatan Daya Saing PTS
PTS harus berinovasi dengan menawarkan prodi yang relevan dengan kebutuhan industri, seperti teknologi blockchain, analitik data, atau pariwisata berkelanjutan. Kemitraan dengan sektor swasta, seperti yang dilakukan oleh Universitas Bina Nusantara dengan perusahaan teknologi, dapat menjadi model. Konsorsium PTS, seperti yang dikoordinasikan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dapat membantu PTS kecil berbagi sumber daya, seperti dosen tamu, laboratorium bersama, atau platform pembelajaran daring.
Pemerataan Akses Pendidikan:
Program KIP-K harus diperluas untuk mendukung mahasiswa di PTS, dengan mekanisme pengawasan ketat untuk memastikan tepat sasaran. Kampanye publik juga diperlukan untuk mengubah persepsi bahwa PTS berkualitas dapat bersaing dengan PTN, terutama jika memiliki akreditasi baik dan kemitraan industri yang kuat. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan skema beasiswa khusus untuk mahasiswa PTS di daerah tertinggal.
Pencabutan Moratorium PTS Baru Secara Selektif
Moratorium pembukaan PTS baru sejak 2018 dapat dicabut secara selektif untuk memungkinkan masuknya PTS baru yang inovatif dan berkualitas, dengan syarat ketat seperti akreditasi awal, komitmen terhadap riset, dan fokus pada kebutuhan lokal. Hal ini akan mendorong persaingan sehat dan memperluas akses pendidikan tinggi di daerah tertinggal.
Pemetaan Kebutuhan Regional
Pemerintah perlu melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan tinggi di setiap wilayah untuk memastikan distribusi PTN dan PTS yang seimbang. Misalnya, di daerah dengan sedikit PTN, PTS dapat didorong untuk mengisi kekosongan dengan prodi yang relevan dengan ekonomi lokal, seperti agribisnis di wilayah agraris atau teknologi maritim di wilayah pesisir.
Kesimpulan
Fenomena “pukat harimau” PTN, dengan jalur pendaftaran yang menjaring semua segmen calon mahasiswa dan prodi baru yang belum teruji, telah menciptakan ketimpangan yang mengancam keberlangsungan PTS dan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia. Kebijakan Mendiktisaintek untuk membatasi penerimaan mahasiswa PTN hingga Juli 2025 adalah langkah reaktif dan dangkal yang tidak menangani akar masalah, seperti ketimpangan sumber daya, persepsi masyarakat, atau regulasi yang tidak seimbang. Solusi ideal memerlukan regulasi ketat untuk membatasi jalur pendaftaran PTN, evaluasi prodi baru, dukungan finansial untuk PTS, peningkatan daya saing PTS melalui inovasi dan kemitraan, pemerataan akses pendidikan, dan pencabutan moratorium PTS baru secara selektif. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan tinggi yang inklusif, kompetitif, dan relevan dengan tantangan global, memastikan bahwa PTN dan PTS dapat berkontribusi secara seimbang bagi kemajuan bangsa.