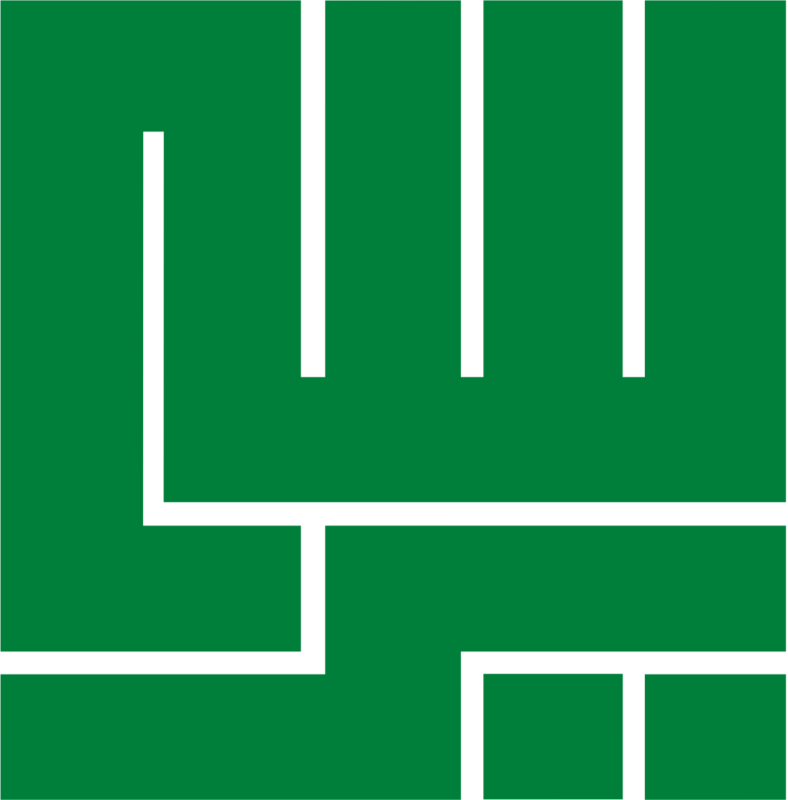BANJIR dan longsor besar yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 bukan sekadar berita duka—ia adalah “laporan audit” yang ditulis alam dengan tinta lumpur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu 30 November menyatakan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 316 orang, dan 289 orang dilaporkan hilang.
Secara ilmiah, hubungan antara deforestasi dan bencana hidrometeorologi bukan mitos aktivis—itu mekanika lanskap. Hutan tropis berfungsi seperti “infrastruktur hijau”: kanopi menahan intensitas hujan, akar memperkuat tanah, serasah meningkatkan infiltrasi, dan bentang alam memperlambat limpasan.
Ketika tutupan hutan dibuka (untuk jalan, kebun skala besar, tambang, ataupun pembalakan), air hujan lebih cepat menjadi limpasan; erosi meningkat; sungai tersedimentasi; kapasitas tampung turun; dan di lereng curam, longsor menjadi lebih mungkin. Cuaca ekstrem tetap penting, tetapi ia berubah dari “hujan lebat” menjadi “banjir bandang” karena lanskap kehilangan peredamnya.
Di Sumatera Barat, WALHI menegaskan bencana ini “bencana ekologis, bukan bencana alam,” sambil mengaitkannya dengan rusaknya hulu DAS dan lemahnya penegakan tata ruang. Mereka juga memaparkan angka kehilangan tutupan hutan yang besar: 320 ribu hektare hutan primer lembap hilang (2001–2024), dan deforestasi 2024 sekitar 32 ribu hektare. Ketika indikator ekologis separah itu, yang “meledak” di hilir hanyalah konsekuensi yang tertunda.
Di Aceh, nada serupa juga muncul. WALHI Aceh menyebut banjir berulang sebagai hasil akumulasi deforestasi, ekspansi sawit, aktivitas tambang, hingga PETI, serta menyorot kerusakan DAS (termasuk DAS Krueng Peusangan) yang berdampak ke wilayah hilir. Mereka juga mencatat sedimentasi sungai mempercepat luapan saat hujan deras. Ini tentu poin penting di mana kerusakan hutan dan sekaligus lingkungan sungai adalah “dua bilah gunting” yang sama-sama memotong daya tampung ekosistem.
Di Sumatera Utara, WALHI menyebut bahwa banjir bandang dan longsor di wilayah Tapanuli sebagai “bencana ekologis” dan menautkannya dengan pembukaan tutupan hutan di sekitar Ekosistem Batang Toru—wilayah penyangga hidrologis yang krusial.
Media massa juga melaporkan bahwa WALHI Sumut bahkan menuding keterlibatan perusahaan-perusahaan ekstraktif dan menuntut evaluasi serta penegakan hukum yang lebih keras. Mongabay juga memuat pernyataan kepala daerah setempat yang mengaitkan bencana dengan alih fungsi hutan, sawit, dan illegal logging, serta menegaskan bahwa curah hujan tinggi tak lagi “tertahan” di hulu.
Catatan skeptis yang sehat yaitu “diduga deforestasi” tidak boleh berubah menjadi vonis tanpa investigasi hidrologi dan tata kelola yang rapi. Namun, ketika pola narasinya konsisten lintas provinsi—hulu rusak, DAS rapuh, sedimentasi tinggi, tata ruang longgar—maka hipotesis deforestasi sebagai faktor struktural menjadi sangat masuk akal, bahkan sebelum kita masuk ke detail pelaku per lokasi.
Ekonomi Sesaat vs Kerugian Jangka Panjang
Mengapa pola bencana ini terus berulang? Karena ekonomi sering memberi hadiah untuk yang cepat, bukan yang benar. Eksploitasi hutan tropis (kayu, pulp, perkebunan, tambang) menghasilkan arus kas dan PDRB yang tampak rapi di laporan tahunan.
Tetapi pada saat yang sama, ia memindahkan biaya ke “rekening publik”: jembatan putus, sawah tertimbun, sekolah rusak, penyakit pascabanjir, hilangnya hari kerja, dan trauma sosial. Ini adalah externalities klasik—biaya nyata yang tidak dibayar oleh pelaku, tetapi ditanggung masyarakat.
Data deforestasi nasional menunjukkan persoalan ini bukan anekdot. Pemerintah (melalui kanal kehutanan.go.id) menyebut deforestasi netto 2024 sekitar 175,4 ribu hektare (deforestasi bruto 216,2 ribu hektare dikurangi reforestasi 40,8 ribu hektare).
BPS juga menyediakan seri statistik deforestasi netto Indonesia (di dalam dan di luar kawasan hutan) untuk 2013–2022. Angka-angka ini tidak otomatis menjelaskan banjir spesifik di satu kabupaten—tetapi data ini menggambarkan “anggaran” kehilangan tutupan hutan yang menumpuk terus dari tahun ke tahun.
Di titik ini, suara aktivis menjadi relevan bukan karena retorikanya, melainkan karena ia sering membaca pola tata kelola yang luput dari statistik. Greenpeace, misalnya, menyorot kontradiksi kebijakan: banyak aturan perlindungan lingkungan ada, namun implementasinya lemah dan izin ekstraktif terus berjalan.
Dalam laporan media massa, perwakilan Greenpeace menyebut ketiadaan peta jalan pemulihan hutan dan ekspansi konsesi sebagai faktor yang membuat bencana kian sering, sembari mengkritik ketidak-konsistenan pemerintah dalam menegakkan aturan. Mereka juga secara eksplisit menyebut banjir di Sumut–Sumbar–Aceh sebagai “wajah krisis” yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar cuaca buruk semata.
Secara konsep ekonomi lingkungan, inti masalahnya adalah salah dalam desain insentif. Ketika keuntungan dari pembukaan lahan cepat diprivatisasi, sementara risiko banjir dan longsor disosialisasi, maka “pasar” akan secara rasional memilih pembukaan lahan.
Solusinya tentu bukan sekadar menanam pohon seremonial, melainkan mengubah struktur keputusanya itu audit dan penertiban izin di hulu DAS, moratorium yang benar-benar efektif pada kawasan bernilai lindung, restorasi riparian, penegakan hukum pada pelanggaran (legal maupun ilegal), serta transparansi citra satelit yang bisa diawasi publik. Tentu saja yang paling sulit adalah mengakui hutan sebagai aset produktif (natural capital), bukan “lahan menganggur” yang harus segera dimonetisasi secara ugal-ugalan.
Siapa yang diuntungkan?
Korporasi dan pemilik modal meraup keuntungan jangka pendek. Siapa yang menanggung kerugian jangka panjang? Tentu masyarakat lokal, generasi mendatang, serta lingkungan hidup yang hancur. Ini adalah transaksi ketidakadilan intergenerasional—hutan dan kelestarian alam dikorbankan demi keuntungan cepat.
Banjir dahsyat di Aceh, Sumut, dan Sumbar atau beberapa daerah lainnya hanyalah pengingat bahwa alam punya mekanisme penagihan khas yaitu cepat, mahal, mematikan dan juga tak bisa dinegosiasikan. Kita boleh saja berdebat panjang tentang porsi kontribusi cuaca ekstrem vs kerusakan hutan pada satu peristiwa, tetapi arah kebijakannya jelas—memulihkan fungsi hulu DAS dan menutup “kebocoran tata kelola” jauh lebih murah daripada membangun kembali kota yang berkali-kali ditenggelamkan.
Jika ekonomi dan ekosistem ingin tetap rasional, bukan serakahnomics, tentu kita harus berhenti menganggap hutan sebagai saldo yang boleh dikurangi tanpa batas—karena tiap hektare yang hilang pada akhirnya berubah menjadi risiko yang pulang ke rumah kita sendiri.
Prof. Perdana Wahyu Santosa
Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific