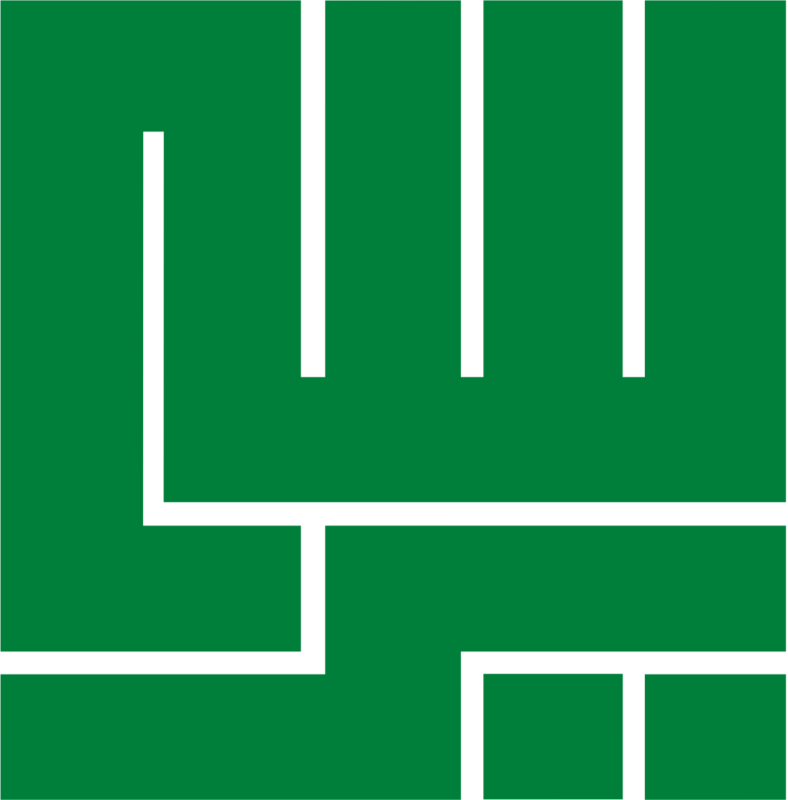TAMPAKNYA setiap keputusan Bank Indonesia (BI) tentang suku bunga acuan selalu menjadi semacam detak jantung bagi perekonomian nasional. Ketika BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen pada Oktober 2025, publik langsung menafsirkan banyak hal, sekurangnya: inflasi masih terkendali, pertumbuhan cukup moderat, dan stabilitas rupiah tetap diprioritaskan.
Tetapi di balik angka yang tampak sederhana itu, pastinya tersembunyi jaringan keputusan yang kompleks. Suku bunga adalah pesan kepada pasar uang, investor, dan rumah tangga. Ketika BI menahan bunga, ia sesungguhnya sedang menimbang antara dua sisi neraca kebijakan krusial -stabilitas dan pertumbuhan.
Secara global, ekonomi 2025 bukan tahun yang mudah. Ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok, serta fluktuasi harga energi dan pangan terus menciptakan gelombang ketidakpastian. Amerika Serikat mulai menurunkan suku bunga setelah periode pengetatan panjang, sementara Eropa masih berhati-hati. Dalam lanskap ini, Indonesia memilih sikap konservatif-adaptif: tidak terburu-buru memacu pertumbuhan lewat pelonggaran moneter, tetapi juga tidak membiarkan bunga tinggi menahan kredit produktif terlalu lama.
Keputusan BI ini bisa dibaca sebagai strategi “menunggu dengan arah yang jelas”. Bank sentral tidak menutup kemungkinan penurunan bunga ke depan, tetapi ia ingin memastikan fondasi makroekonomi cukup kuat. Prinsip dasarnya sederhana: menstabilkan nilai tukar terlebih dahulu sebelum melonggarkan likuiditas, sebab kestabilan rupiah sering kali lebih menentukan persepsi kepercayaan pasar dibandingkan sekadar angka pertumbuhan.
Suku Bunga Turun, Ekonomi Naik?
Mari kita bahas, ada pandangan umum -yang sering kali berlebihan- bahwa jika suku bunga turun, ekonomi akan otomatis tumbuh. Secara teori memang sah dan benar: bunga yang rendah menurunkan biaya pinjaman, mendorong konsumsi dan investasi, terjadi multiplier effect dan akhirnya memperluas lapangan kerja. Namun dalam praktiknya, terkadang hubungan itu tidak selalu sejalan. Mengapa?
Pertama, transmisi kebijakan moneter tidak langsung. Dari keputusan BI hingga perubahan suku bunga kredit di bank komersial, biasanya ada jeda waktu (lag) dan muncul resistensi. Bank tetap mempertimbangkan risiko kredit dan kecukupan modal sebelum menurunkan bunga pinjaman. Banyak pelaku usaha mengeluh bahwa suku bunga acuan turun, tetapi bunga kredit belum ikut melandai.
Kedua, perilaku pelaku ekonomi turut menentukan efektivitas kebijakan. Ketika kondisi global tidak menentu, perusahaan besar cenderung menahan ekspansi meskipun kredit murah. Mereka memilih memperkuat arus kas daripada berinvestasi di sektor yang belum pasti permintaannya. Rumah tangga pun bisa bersikap hemat: menabung lebih banyak, berbelanja lebih sedikit.
Ketiga, ada faktor psikologis dan struktural. Konsumen tidak hanya bereaksi terhadap bunga, tetapi terhadap ekspektasi masa depan: apakah lapangan kerja aman, harga stabil, dan pemerintah kredibel? Tanpa rasa aman, stimulus moneter bisa “mengalir ke tempat yang salah”: menumpuk di deposito atau pasar keuangan, bukan ke sektor riil.
Indonesia juga pernah mengalami paradoks semacam ini. Pada masa pandemi 2020?”2021, BI menurunkan bunga hingga level terendah 3,5 persen, namun kredit produktif tak melonjak. Banyak perusahaan justru melunasi pinjaman atau menahan investasi. Artinya, kebijakan moneter hanya efektif bila ada kepercayaan bahwa masa depan ekonomi bisa ditebak dan risiko bisa dikendalikan.
Stabilitas dan Pertumbuhan
Dalam konteks ini, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level moderat bisa dibaca bukan sebagai keengganan, melainkan sebagai kehati-hatian strategis. Ada tiga alasan utama mengapa strategi ini patut dipahami secara proporsional.
Pertama, stabilitas rupiah tetap menjadi benteng utama. Dengan defisit transaksi berjalan yang relatif rendah dan cadangan devisa di atas USD130 miliar, tekanan eksternal memang berkurang, tetapi sentimen global dapat berubah cepat. Ketika modal asing keluar dalam jumlah besar (seperti arus keluar Rp 2,7 triliun di akhir September 2025), nilai tukar bisa tertekan. Bunga yang terlalu rendah justru memperbesar risiko ini.
Kedua, inflasi inti Indonesia masih dalam koridor aman (sekitar 2,6?”2,8 persen) -tetapi tekanan harga pangan dan energi tetap ada. Dalam situasi ini, BI memilih menjaga kredibilitas inflasi: lebih baik sedikit ketat daripada kehilangan kepercayaan pasar. Jika inflasi tak terkendali, biaya sosial-ekonomi bisa jauh lebih tinggi daripada kehilangan sedikit pertumbuhan jangka pendek.
Ketiga, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal kini jauh lebih baik dibanding satu dekade lalu. Pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur dan perlindungan sosial untuk menahan perlambatan, sementara BI memastikan likuiditas perbankan cukup. Pola ini mencerminkan pergeseran filosofi: bukan hanya soal “tinggi-rendah bunga”, tetapi bagaimana menjaga irama kebijakan agar tidak saling meniadakan.
Keseimbangan ini sangat penting di tengah transformasi ekonomi. Indonesia sedang beralih dari ekonomi berbasis komoditas ke industri bernilai tambah dan digital. Pertumbuhan yang berkelanjutan butuh stabilitas jangka panjang, bukan euforia jangka pendek. Suku bunga bukan pedal gas; ia adalah kemudi yang menentukan arah.
Penutup
Dalam politik ekonomi, menahan diri sering kali lebih sulit daripada bertindak. Menurunkan bunga bisa membuat headline media lebih optimistis, tetapi menjaga kestabilan di tengah badai adalah keputusan yang lebih berani. Kebijakan moneter yang baik tidak diukur dari seberapa sering berubah, melainkan dari seberapa dipercaya ia menjaga arah ekonomi. BI tampaknya sedang menulis bab baru dalam kebijakan ekonomi Indonesia: bab di mana ketenangan menjadi strategi, bukan kelemahan. Di tengah ketidakpastian global, sikap BI ini pantas diapresiasi -asalkan diikuti reformasi struktural yang membuat kredit benar-benar produktif, investasi makin mudah, dan masyarakat punya kepercayaan terhadap masa depan ekonomi mereka. Pada akhirnya, fungsi utama suku bunga bukan hanya mengatur harga uang, tetapi juga menyalakan sinyal kepercayaan, memicu optimisme. Dan dalam ekonomi modern, kepercayaan dan optimisme adalah mata uang yang nilainya sering kali lebih kuat daripada rupiah itu sendiri.
Perdana Wahyu Santosa
Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute.