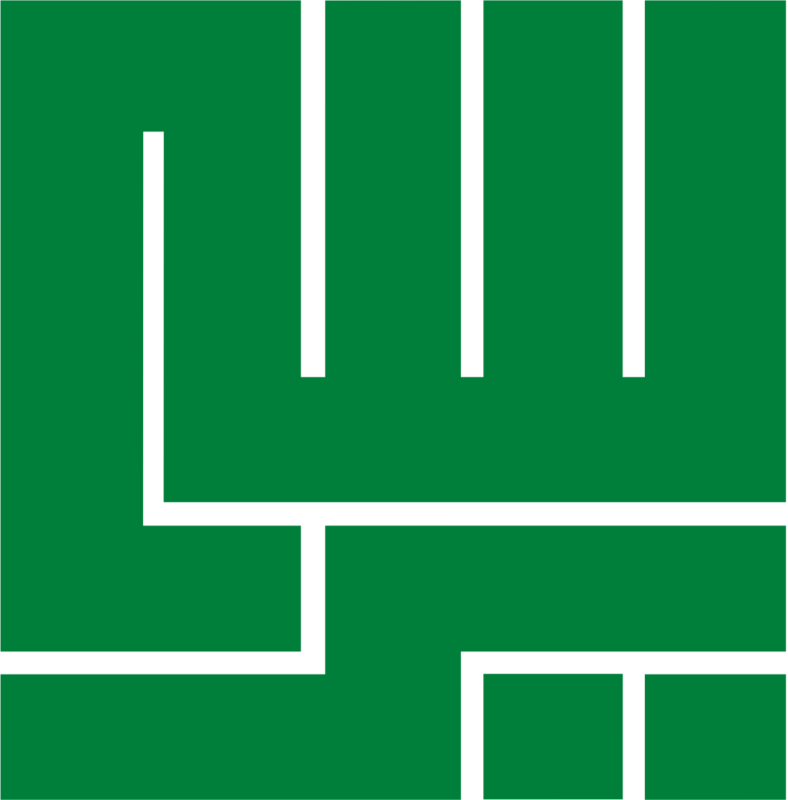JERNIH– Indonesia memasuki 2025 dengan pasar kerja yang tampak sehat dan baik-baik saja di permukaan, namun menyimpan sinyal halus soal kualitas penyerapan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 turun menjadi 4,85 persen—sekitar lima dari 100 angkatan kerja belum terserap—lebih rendah 0,06 persen poin dibanding Agustus 2024. Itu kabar baik, tetapi tidak cukup untuk menutup cerita penuh dari pasar kerja kita.
Mari kita coba bedah anatominya. Angkatan kerja mencapai 154,00 juta orang; yang bekerja 146,54 juta; TPAK 70,59 persen. Di sisi penawaran tenaga kerja, ini menunjukkan partisipasi relatif tinggi dan tetap, seiring bertambahnya PUK menjadi 218,17 juta. Namun kualitas penyerapan—apakah pekerja bekerja “sepenuh” kapasitas keahliannya dan jam kerja— menjadi isu kunci.
Upah dan Lompatan Keterampilan
Upah rata-rata buruh pada Agustus 2025 berada di Rp3,33 juta per bulan. Kesenjangan gender masih nyata: rata-rata laki-laki Rp3,59 juta, perempuan Rp2,86 juta. Perbedaan ini bukan sekadar angka; ia menyiratkan struktur kesempatan dan negosiasi upah yang tidak simetris, serta potensi perbedaan sektor dan jenis pekerjaan yang ditempati laki-laki dan perempuan.
Soal sektor, Informatika dan Komunikasi memimpin upah (Rp5,28 juta), disusul Keuangan dan Asuransi (Rp5,12 juta) serta Pengadaan Listrik dan Gas (Rp5,07 juta). Di ujung lain, “Aktivitas Jasa Lainnya” hanya Rp1,97 juta—mencerminkan segmen jasa berupah rendah yang padat karya dan sering informal. Ketimpangan lintas-sektor ini menandai ekonomi yang semakin berbasis pengetahuan: premi upah menempel pada kompetensi digital, jasa keuangan, dan utilitas berteknologi.
Dimensi pendidikan memperkuat cerita: lulusan diploma IV/S1/S2/S3 menerima sekitar 2,2 kali upah lulusan SD ke bawah. Tetapi “pendidikan” mesti dibaca sebagai keterampilan relevan—terutama digital, analitik, dan layanan bernilai tambah. Tanpa last-mile training yang menutup skills gap, premium upah akan terkunci pada segelintir kelompok.
Underemployment: Banyak Kerja, Jam Belum Cukup
Titik paling “unik” dari potret 2025 bukan pada pengangguran atau upah semata, melainkan waktu kerja. Proporsi pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam/minggu) meningkat dibanding 2024; pekerja paruh waktu naik, sementara setengah penganggur hanya sedikit menurun. Ini memberi sinyal ganda: lebih banyak orang punya pekerjaan, tetapi sebagian semakin “pendek” jamnya—sebuah pasar kerja penuh tapi tak penuh.
Dari sudut kebijakan publik, fokus mulai bergeser dari “ciptakan pekerjaan” menjadi ciptakan jam kerja dan produktivitas yang cukup. Ini menyentil desain pasar tenaga kerja yang terlalu puas pada statistik TPT, padahal kerentanan daya beli rumah tangga sering berawal dari jam kerja yang tak penuh—bukan dari ketiadaan pekerjaan sama sekali.
Mobilitas Komuter
Tercatat sebanyak 7,69 juta orang—sekitar 5,25 persen dari seluruh pekerja—bolak-balik lintas kabupaten/kota dalam hari yang sama. Fenomena ini paling tebal di wilayah metropolitan: Jabodetabekpunjur mencatat porsi komuter tertinggi, diikuti Sarbagita dan Banjarbakula.
Komuter adalah “biaya friksi” yang muncul efek pertumbuhan—ia menambah peluang kerja lintas batas administrasi, tetapi juga menuntut infrastruktur transportasi, tata ruang, dan koordinasi lintas daerah yang cermat.
Mayoritas komuter bekerja di kegiatan formal (di atas 80 persen) dan memakai kendaraan pribadi/dinas (sekitar 90 persen), meski ada kenaikan kecil pengguna transportasi umum. Ini menyiratkan preferensi yang masih berat ke mobilitas privat—dengan implikasi kemacetan, emisi, dan beban biaya rumah tangga. Efektivitas kebijakan tarif terpadu, park-and-ride, dan integrasi antarmoda menjadi faktor pembalik.
Kebijakan yang bisa ditarik?
- Dari “banyak kerja” ke “cukup jam dan produktif”. Penurunan TPT patut diapresiasi, namun kenaikan pekerja paruh waktu menuntut kebijakan peningkatan jam kerja efektif. Instrumen yang relevan: insentif adopsi teknologi untuk UMKM agar memperluas jam dan nilai tambah; shift marketplace lokal untuk matching jam kerja; serta pelatihan mikro- modular agar pekerja menambah jam di sektor berproduktivitas tinggi tanpa switching cost besar.
- Premium upah = lompatan Skema last-mile training yang menghubungkan vokasi dengan kebutuhan sektor IKT, keuangan, dan utilitas akan memperkecil skills gap. Targetkan sertifikasi cepat (≤12 minggu) untuk data support, jaringan, QA, customer success, dan teknisi utilitas—bidang yang menyumbang premi upah paling jelas.
- Mobilitas metropolitan adalah kebijakan pasar Ketika belasan persen pekerja di Jabodetabekpunjur adalah komuter, kualitas angkutan umum, hunian terjangkau dekat pusat kerja, dan jam kerja fleksibel berdampak langsung pada produktivitas. Dorong WFH/Hybrid selektif bagi pekerjaan formal tertentu untuk mengempiskan beban infrastruktur pada jam puncak tanpa menurunkan output.
- Tutup celah upah gender dengan kombinasi kebijakan keras–lunak. Mulai terapkan transparansi kisaran upah per jabatan, audit kesetaraan upah di BUMN dan perusahaan besar, serta perluas layanan penitipan anak Ini bukan hanya isu keadilan; ini soal total factor productivity.
- Naikkan kualitas kerja informal sambil mendorong Porsi formal memang meningkat tipis, tetapi mayoritas pekerja masih informal. Rancang iuran jaminan sosial mikro, kontrak standar sederhana, dan insentif pajak untuk formalitas tahap awal (misalnya tax allowance berbasis serapan tenaga kerja penuh-waktu) agar kualitas kerja naik tanpa mematikan usaha kecil.
- Diversifikasi sumber kenaikan upah. Selama setahun, upah rata-rata naik moderat; sebagian sektor strategis bahkan turun, mengikuti siklus komoditas dan teknologi. Re- skilling lintas-sektor adalah asuransi karier: ketika pertambangan melandai, pekerja bisa bermigrasi ke utilitas listrik terbarukan, manufaktur berorientasi ekspor, atau jasa digital dengan masa depan cerah.
Penutup
Di balik statistik BPS yang tampak “aman”, Indonesia sedang mengelola transisi pasar kerja: dari kuantitas ke kualitas, dari pekerjaan apa saja ke pekerjaan dengan jam cukup dan upah layak, dari mobilitas privat ke sistemik, dari ketimpangan gender ke kesetaraan produktif. TPT yang turun itu penting tentunya; tetapi pekerjaan publik sesungguhnya adalah memastikan pasar kerja kita penuh, bukan sekadar tak menganggur.
Itu berarti mengikat kebijakan ketenagakerjaan dengan transportasi, perumahan, pendidikan, dan inovasi—sebuah orkestra lintas sektor yang akan menentukan daya saing Indonesia di dekade ini. [ ]
Perdana Wahyu Santosa
Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute