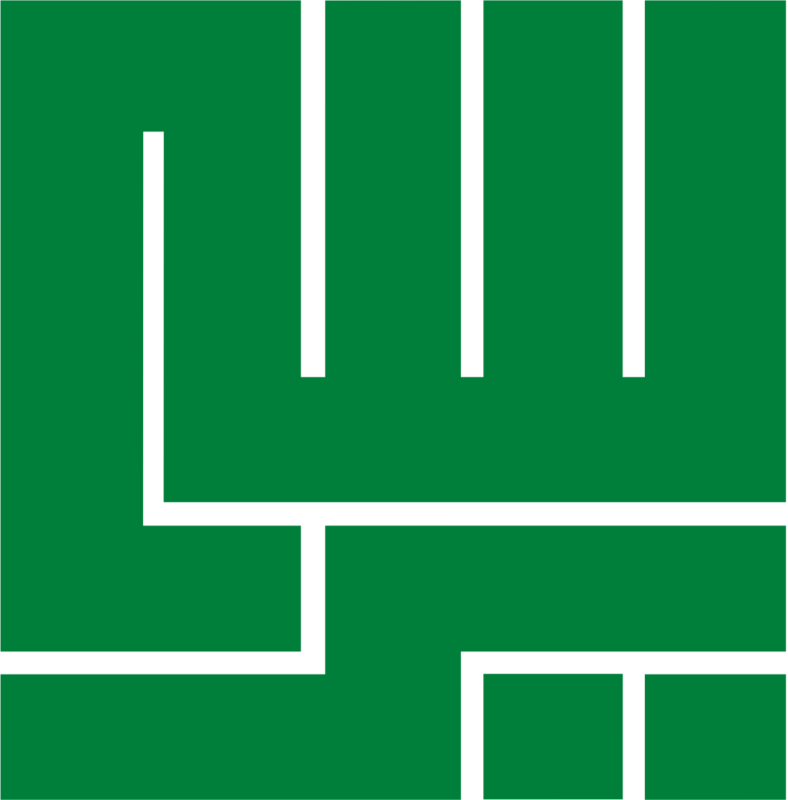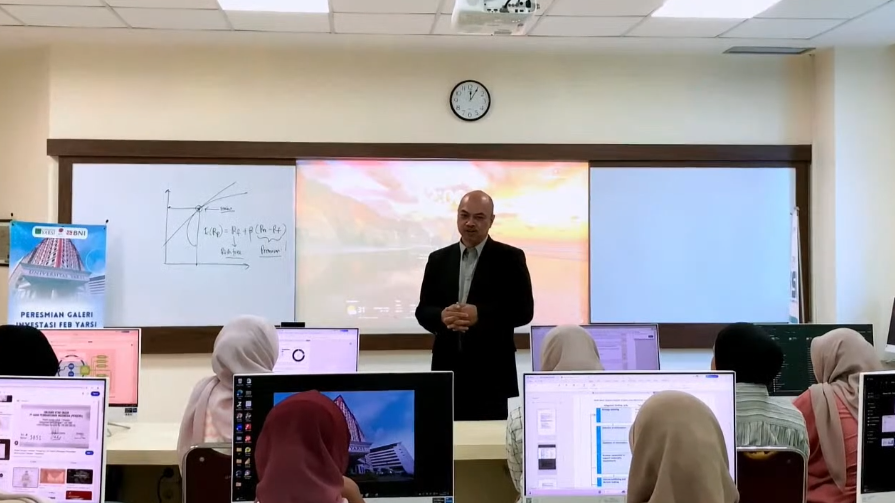Dalam satu dekade terakhir ini, Indonesia mengalami revolusi sosial paling besar sejak reformasi 1998– tetapi tanpa teriakan demonstrasi, tanpa manifesto politik, dan juga tanpa pemimpin karismatik.
Revolusi itu hanya berlangsung di layar gawai, dipicu oleh koneksi internet dan media sosial. Data We Are Social menunjukkan, pada tahun 2025 jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 212 juta orang (penetrasi 74,6% populasi), sementara pengguna media sosial aktif mencapai 143 juta.
Angka ini menjadikan Indonesia salah satu masyarakat digital terbesar di dunia. Namun di balik euforia ini, revolusi digital membawa dampak ekonomi, sosial, dan politik yang jauh lebih dalam daripada yang kita sadari.
Konsumen dalam Ekonomi Aktif
Teknologi jelas telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat Indonesia secara fundamental. Dalam ekonomi pra-digital, aktivitas ekonomi bersifat lokal dan fisik. Kini, transaksi berpindah ke ruang maya, diatur oleh algoritma yang menentukan apa yang kita lihat, beli, dan pikirkan.
Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop telah menciptakan generasi konsumen yang berinteraksi dengan pasar hingga 24 jam sehari — bukan lagi melalui toko, tetapi lewat feed yang dikurasi.
Fenomena ini melahirkan apa yang disebut “algorithmic consumption”, di mana setiap keputusan ekonomi tidak lagi murni berdasarkan kebutuhan, melainkan akibat dorongan algoritmik yang memanfaatkan data perilaku pengguna. Produk, iklan, bahkan opini politik disesuaikan dengan preferensi individu, tentunya.
Dalam jangka pendek, model ini meningkatkan efisiensi pasar; dalam jangka panjang, ia menimbulkan risiko baru: hilangnya otonomi konsumen dan monopoli informasi oleh raksasa teknologi digital.
Faktanya, konsekuensi makroekonominya tercatat signifikan. Sektor digital telah menyumbang lebih dari 7% PDB Indonesia pada 2024, dan diproyeksikan mencapai 12% pada 2030.
Namun, sebagian besar nilai tambah ekonomi itu terkonsentrasi pada perusahaan global seperti Meta, Google, dan ByteDance. Pajak digital yang baru diberlakukan masih belum mampu menutup value leakage lintas batas.
Indonesia membutuhkan kebijakan fiskal digital yang lebih progresif: digital transaction
tax dan data value sharing agar ekonomi digital benar-benar menciptakan pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar ketergantungan baru.
Pendidikan Semakin Terhubung?
Era digital telah membuka akses informasi tak terbatas bagi generasi muda. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa kelompok Gen-Z dan milenial mencakup lebih dari 65% pengguna internet nasional.
Anak sekolah kini lebih cepat mengakses konten YouTube daripada membaca buku teks. Aplikasi ed-tech dan platform pembelajaran daring menjanjikan pendidikan yang inklusif dan fleksibel.
Namun ironisnya kemajuan teknologi tidak selalu berarti peningkatan kualitas belajar. Banyak riset menunjukkan bahwa screen time yang tinggi sering berbanding terbalik dengan kemampuan berpikir kritis.
Literasi digital Indonesia masih rendah — menurut UNESCO, hanya 28% siswa mampu membedakan informasi kredibel dan palsu. Fenomena edutainment (pendidikan sebagai hiburan) mendorong pelajar lebih fokus pada kecepatan informasi ketimbang kedalaman pemahaman.
Selain itu, ketimpangan digital juga memperlebar jurang antarwilayah. BPS 2024 mencatat bahwa penetrasi internet di DKI Jakarta mencapai 87,8%, sementara Papua masih di bawah 50%. Artinya, revolusi digital belum sepenuhnya merata.
Ketika sekolah di kota besar bertransformasi menuju kelas hybrid dan AI-assisted learning, ribuan sekolah di pelosok masih berjuang dengan sinyal lemah dan keterbatasan perangkat. Jika pendidikan digital tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif, maka alih-alih memperkecil kesenjangan sosial, teknologi justru bisa memperdalamnya.
Struktur Sosial Baru
Dampak sosial media tidak hanya terbatas pada konsumsi dan politik, tetapi juga pada struktur ekonomi. Generasi muda kini membangun karier di ruang digital: influencer marketing, content creator economy, online trading, dan freelance platform. Lapangan kerja formal bergeser ke pekerjaan berbasis algoritma — diatur oleh sistem rating, bukan hubungan kerja tradisional.
Di satu sisi, fenomena ini meningkatkan fleksibilitas dan peluang pendapatan. Di sisi lain, ia menciptakan bentuk baru ketidakpastian ekonomi: digital precariat — pekerja digital tanpa perlindungan sosial, tanpa kontrak tetap, dan bergantung pada sistem platform.
Koperasi, serikat pekerja, dan sistem jaminan sosial kita belum siap menghadapi realitas ini. Program seperti BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencakup pekerja ekonomi digital.
Padahal, mereka adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi baru. Jika negara gagal mengadaptasi kebijakan ketenagakerjaan dan pajak, maka kesenjangan antara ekonomi formal dan digital akan semakin dalam.
Literasi, Regulasi, dan Etika Digital
Indonesia agaknya tidak sedang kekurangan teknologi, tetapi kekurangan etika dan literasi digital. Revolusi sosial media yang semula menjanjikan demokrasi partisipatif kini berubah menjadi ekonomi atensi — di mana yang paling cepat dan paling keras mendapat panggung, sementara yang reflektif tenggelam.
Kebijakan publik perlu beradaptasi. Pertama, regulasi platform digital harus menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial. Pemerintah harus bernegosiasi secara lebih setara dengan raksasa teknologi global untuk memastikan transparansi algoritma dan pajak yang adil.
Kedua, literasi digital kritis harus masuk dalam kurikulum sejak sekolah dasar, bukan hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi cara memahami dan menilai informasi.
Selanjutnya ketiga, pemerataan infrastruktur digital wajib menjadi agenda keadilan sosial baru. Konektivitas bukan sekadar soal sinyal, tetapi hak untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan demokrasi digital.
Penutup
Dalam sinergi antara literasi, regulasi, dan etika digital pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri; selain itu dunia pendidikan juga perlu menanamkan digital
ethics sebagai mata ajaran wajib, dan sektor swasta juga harus mematuhi prinsip tech for humanity, bukan sekadar tech for profit. Dalam konteks ini, kolaborasi antara negara, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci.
Revolusi digital di Indonesia berlangsung tanpa guntur politik, tetapi dengan efek seismik pada masyarakat. Ia mengubah cara kita membeli barang, belajar, bekerja, dan berpendapat. Tetapi tanpa kebijakan yang visioner, revolusi ini bisa menciptakan generasi yang terkoneksi tapi masih terfragmentasi — cerdas secara teknologi, namun miskin refleksi.
Ekonomi digital dan media sosial adalah dua sisi dari koin modernitas terbaru: keduanya membuka peluang luar biasa, sekaligus membawa risiko baru.
Jika Indonesia ingin memanfaatkan revolusi senyap ini untuk memperkuat kesejahteraan dan demokrasi, maka arah pembangunan harus bergeser dari sekadar digital access menuju digital wisdom, karena pada akhirnya, bangsa yang
besar bukanlah bangsa dengan pengguna internet terbanyak, tetapi bangsa yang paling bijak dalam menggunakannya.
Perdana Wahyu Santosa
Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute.