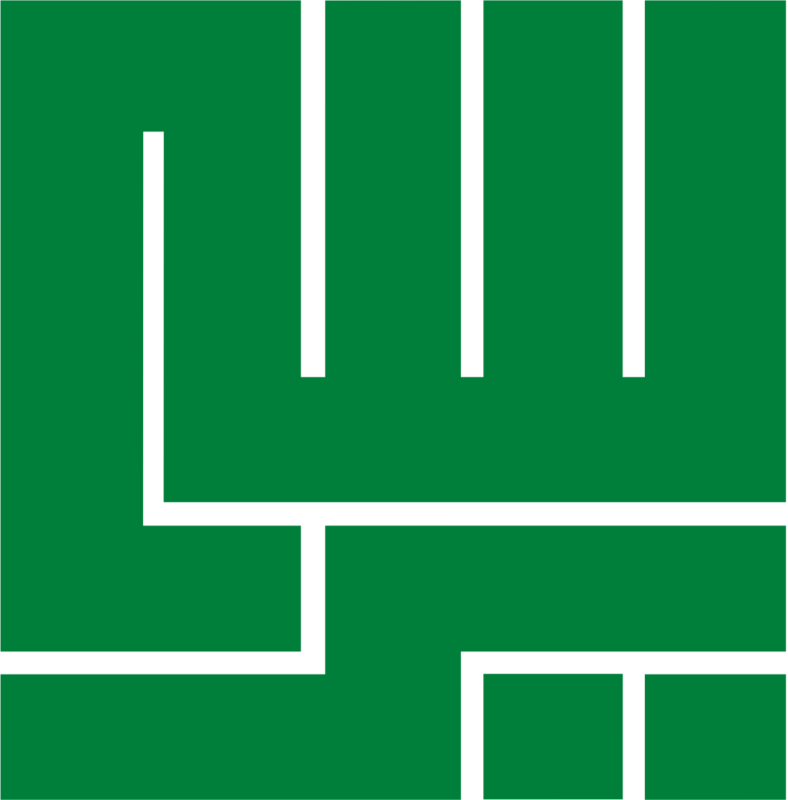Dalam dunia akademik Indonesia, penelitian adalah jantung dari Tridharma Perguruan Tinggi. Seorang dosen atau peneliti tidak hanya wajib menghasilkan penelitian yang bermutu, tetapi juga mempublikasikannya agar pengetahuan baru dapat diakui dan bermanfaat bagi masyarakat. Publikasi ilmiah menjadi tolok ukur keberhasilan akademik, sekaligus cermin kemajuan intelektual sebuah bangsa. Namun, di balik misi mulia ini, dunia publikasi ilmiah Indonesia tampaknya sedang terjangkiti sindroma yang meresahkan: inferior kompleks, di mana kualitas penelitian sering kali dinilai dari nama penulis yang “berbau asing” atau afiliasi kampus luar negeri, bukan dari substansi dan kualitas karya itu sendiri.
Publikasi ilmiah memiliki hierarki yang jelas. Di tingkat global, jurnal terindeks Scopus menjadi standar emas, diakui karena rigor akademiknya. Di dalam negeri, Sistem Indeksasi Nasional Terakreditasi (Sinta) menawarkan gradasi dari Sinta 1 hingga Sinta 5, masing-masing dengan standar ketat dalam hal orisinalitas, metodologi, dan proses peer review. Pengalaman menunjukkan, menembus jurnal Sinta 2 membutuhkan waktu minimal enam bulan, sementara publikasi di jurnal Scopus bisa memakan hingga dua tahun. Belum lagi biaya publikasi yang tidak murah, sering kali mencapai jutaan rupiah, menambah beban bagi peneliti Indonesia yang sudah bergulat dengan keterbatasan dana dan waktu.
Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi internasional digaungkan sebagai solusi strategis. Dosen dan peneliti Indonesia didorong bekerja sama dengan akademisi asing guna meningkatkan kualitas penelitian dan memperluas jangkauan publikasi. Secara prinsip, kolaborasi lintas negara memang membawa manfaat: pertukaran ide, akses ke teknologi canggih, dan peluang masuk ke jurnal bereputasi. Namun, di balik niat baik ini, muncul praktik yang mencerminkan inferioritas akademik yang mengkhawatirkan.
Dalam sebuah percakapan dengan seorang kolega yang memahami seluk-beluk publikasi, terungkap realitas yang menyesakkan. “Pak, kalau manuskrip Bapak ditulis bersama penulis asing, pemuatannya akan lebih cepat dipertimbangkan,” katanya. Ketika ditanya alasannya, jawabannya singkat namun mengguncang: “Itu bagian dari penilaian akreditasi jurnal.” Pernyataan ini bukan sekadar anekdot, melainkan cerminan praktik yang kini marak terjadi. Nama penulis dengan nuansa asing—baik karena kewarganegaraan, afiliasi kampus ternama di luar negeri, atau bahkan nama yang “kedengaran internasional”—sering dianggap sebagai jaminan kualitas, meskipun substansi penelitiannya belum tentu lebih unggul. Bukankah ini tanda bahwa sindroma inferior kompleks telah merasuki dunia publikasi ilmiah kita?
Praktik ini menunjukkan bahwa penilaian kualitas penelitian tidak lagi murni berdasarkan substansi. Sebuah manuskrip yang ditulis oleh peneliti Indonesia, betapapun orisinal dan relevannya, sering kali harus “berdandan” dengan nama asing untuk mendapat perhatian lebih cepat dari editor jurnal. Afiliasi dengan kampus ternama seperti Harvard atau Oxford menjadi “tiket emas”, meskipun kontribusi peneliti asing dalam penelitian tersebut mungkin minim. Ini bukan hanya merendahkan kemampuan peneliti lokal, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam ekosistem akademik. Penelitian tentang isu lokal—seperti keberlanjutan sawit di Kalimantan, inovasi UMKM di Jawa, atau transformasi digital di perkotaan Indonesia—memiliki nilai strategis, tetapi sering kali dianggap “kurang prestisius” hanya karena tidak melibatkan nama atau institusi asing.
Sindroma inferior kompleks ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga budaya yang melemahkan kepercayaan diri akademik nasional. Peneliti Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menghasilkan karya yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga kompetitif di panggung global. Namun, ketika sistem publikasi lebih mengutamakan “kemasan internasional” ketimbang isi, kita secara tidak sadar meremehkan kapabilitas sendiri. Akibatnya, peneliti muda terjebak dalam pola pikir bahwa untuk sukses, mereka harus “bergantung” pada kolaborasi asing, bukan mengasah kualitas penelitian mereka sendiri.
Lalu, bagaimana kita keluar dari jebakan ini? Saatnya dunia publikasi ilmiah Indonesia mengedepankan substansi dan kualitas sebagai satu-satunya tolok ukur. Pertama, sistem penilaian jurnal, baik Sinta maupun internasional, harus direformasi. Editor dan reviewer harus fokus pada orisinalitas, metodologi, dan dampak penelitian, bukan pada nama atau afiliasi penulis. Kedua, perguruan tinggi perlu memperkuat kapasitas peneliti lokal melalui pelatihan menulis akademik, akses ke dana penelitian, dan dukungan infrastruktur seperti basis data dan laboratorium. Ketiga, kolaborasi internasional tetap penting, tetapi harus didasarkan pada kesetaraan. Peneliti Indonesia harus tampil sebagai mitra sejajar, bukan sekadar pelengkap dalam proyek global.
Pemerintah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memiliki peran krusial. Jurnal-jurnal Sinta harus ditingkatkan kualitasnya agar tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional, tanpa mengorbankan identitas lokal. Penelitian tentang kearifan lokal, seperti pengelolaan hutan adat atau teknologi ramah lingkungan, memiliki potensi besar untuk menarik perhatian dunia jika dikemas dengan standar akademik yang tinggi. Selain itu, insentif bagi peneliti yang menghasilkan karya berkualitas tanpa ketergantungan pada nama asing perlu diperluas, misalnya melalui penghargaan atau pendanaan khusus.
Sindroma inferior kompleks dalam publikasi ilmiah adalah tantangan yang harus segera diatasi. Dunia perguruan tinggi Indonesia harus berani melangkah keluar dari bayang-bayang ketergantungan pada nama atau institusi asing. Publikasi ilmiah bukan sekadar soal menembus Sinta atau Scopus, tetapi tentang menciptakan pengetahuan yang bermakna dan relevan. Peneliti Indonesia harus percaya bahwa karya mereka—yang lahir dari kerja keras, kreativitas, dan konteks lokal—mampu bersaing di panggung global tanpa perlu “dipoles” dengan nama asing.
Sebagai penutup, sudah saatnya kita menilai penelitian dari substansi dan kualitasnya, bukan dari siapa penulisnya atau dari mana asal kampusnya. Mari bangun ekosistem akademik yang mandiri, percaya diri, dan berorientasi pada keunggulan. Dengan langkah nyata, dunia publikasi ilmiah Indonesia dapat terbebas dari sindroma inferior kompleks dan menjadi kekuatan intelektual yang disegani dunia.