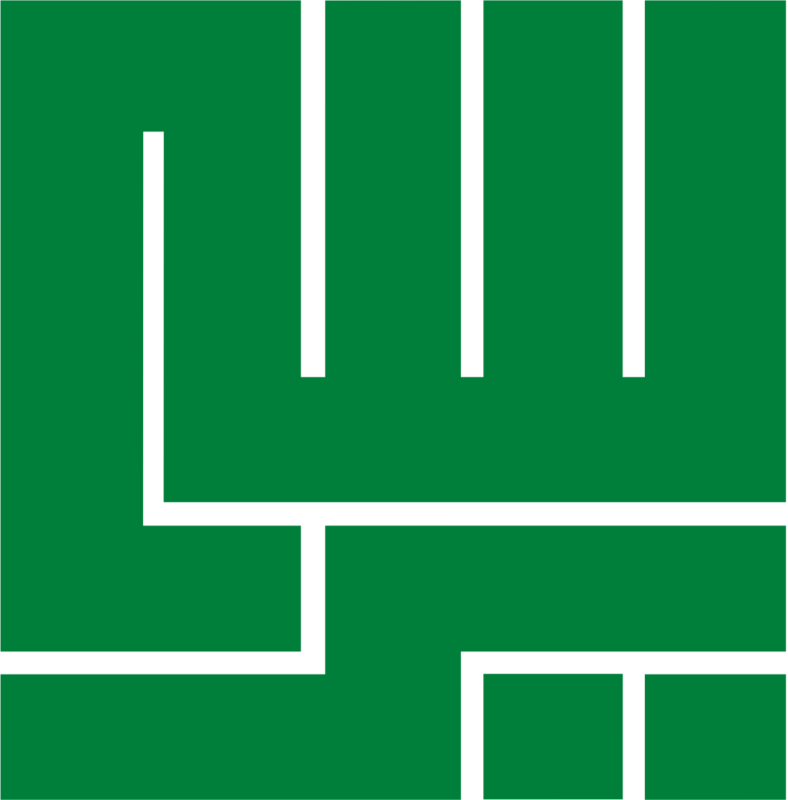Belakangan ini, masyarakat sering dihadapkan pada gambar-gambar aparat penegak hukum yang memamerkan tumpukan uang kertas dalam jumlah fantastis—mulai dari miliaran hingga hampir mencapai angka triliunan rupiah. Fenomena ini menarik untuk dicermati secara kritis, karena tidak hanya melibatkan aspek estetika visual tetapi juga menyimpan pesan sosial dan implikasi hukum yang cukup serius.
Tujuan utama aparat penegak hukum memamerkan uang tersebut biasanya adalah sebagai bukti keberhasilan mereka dalam memberantas tindak pidana korupsi, penggelapan, narkoba, atau kejahatan keuangan lainnya. Dalam konteks ini, eksposur uang dalam jumlah besar dimaksudkan untuk menunjukkan efektivitas kerja aparat, sekaligus memberi sinyal bahwa hukum tidak pandang bulu dalam menangani kasus kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.
Namun, praktik memamerkan uang dalam jumlah sangat besar sebenarnya berada di luar nalar. Secara praktis, tidak mungkin para koruptor atau pelaku kejahatan menyimpan dana secara tunai dalam jumlah sebesar itu. Sudah menjadi kebiasaan di berbagai organisasi dan institusi menggunakan sistem petty cash—yaitu jumlah uang tunai terbatas yang disediakan untuk pengeluaran kecil sehari-hari, bukan menyimpan miliaran rupiah dalam bentuk tunai. Dana hasil kejahatan finansial umumnya disimpan dalam bentuk aset tidak likuid, investasi, atau diputar melalui rekening bank agar lebih sulit dilacak. Oleh karena itu, uang tunai yang dipamerkan biasanya sudah dikumpulkan dari berbagai sumber dan kasus, bukan mencerminkan satu transaksi atau satu pelaku semata.
Misalnya, dalam beberapa kasus besar korupsi di Indonesia, seperti kasus korupsi di proyek e-KTP atau korupsi dana bansos, aparat berhasil menyita uang tunai sejumlah besar yang berasal dari gabungan pendapatan hasil operasi penegakan hukum selama beberapa waktu. Meski jumlahnya sangat besar, uang tersebut bukan disimpan secara mencolok oleh para pelaku, melainkan hasil penelusuran dan penyitaan dari berbagai lokasi atau rekening. Hal ini menguatkan klaim bahwa pemaparan uang dalam jumlah fantastis lebih bersifat simbolik daripada cerminan aktual dari cara koruptor bekerja.
Dari sisi dampak sosial, praktik pamer uang kertas ini seolah menjadi tontonan media yang menghibur publik dan memberikan “kepuasan instan” bahwa hukum sedang bekerja. Namun, pendekatan ini berisiko menimbulkan budaya sensasionalisme yang mengabaikan hak-hak tersangka, proses peradilan yang adil, serta transparansi yang sebenarnya. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, eksibisi tersebut bisa menimbulkan skeptisisme terhadap integritas aparat hukum dan sistem peradilan jika dianggap sebagai pencitraan semata.
Dari perspektif hukum, pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana mekanisme penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan barang bukti berupa uang tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kebocoran. Kelemahan tata kelola barang bukti dapat melemahkan bukti dalam persidangan dan memberi celah bagi oknum mafia hukum. Oleh karena itu, aparat wajib menunjukkan akuntabilitas yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan aset hasil perkara.
Fenomena ini juga mencerminkan dilema institusional di mana aparat penegak hukum terjebak dalam kultur “politik pencitraan” yang lebih mengutamakan narasi keberhasilan dibandingkan proses hukum yang substantif. Dalam negara hukum yang ideal, penegakan hukum haruslah berorientasi pada keadilan yang seimbang, menghormati hak asasi, dan mengedepankan transparansi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip tersebut demi impresi media.
Dengan demikian, fenomena aparat penegak hukum yang suka memamerkan uang kertas dalam jumlah sangat besar sebaiknya ditinjau ulang, tidak hanya dari sisi estetika atau kepuasan publik sesaat, tetapi juga dari implikasi sosial dan hukum yang lebih mendalam. Perlu ada upaya reformasi komunikasi publik aparat agar fokus pada edukasi hukum, transparansi proses, dan akuntabilitas, bukan hanya tontonan angka fantastis yang berpotensi menyesatkan.
Muhammad Akhyar Adnan
Prodi Akuntansi, FEB
Universitas Yarsi