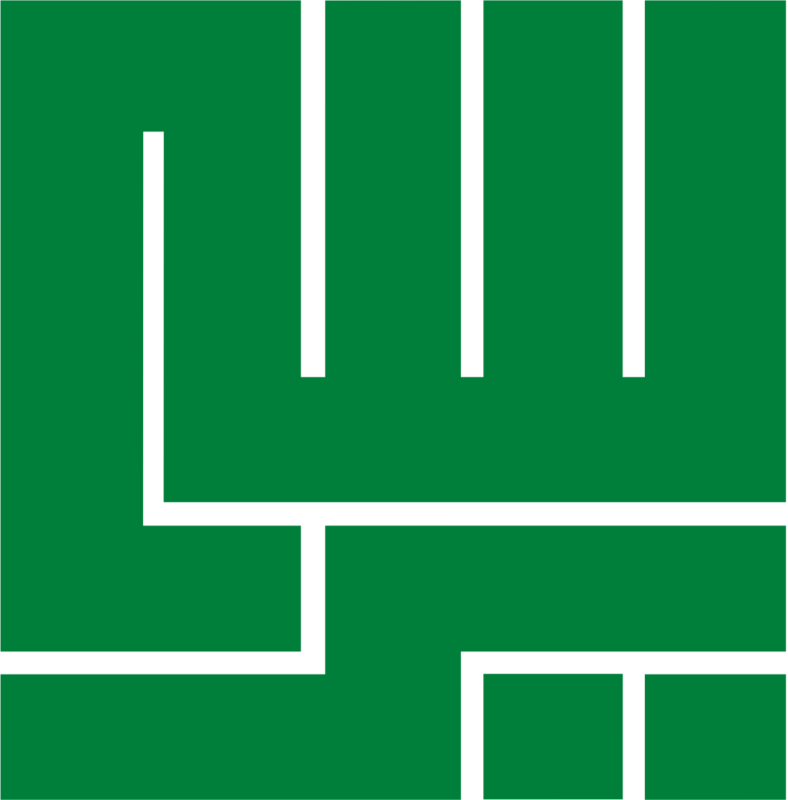Home Opini Fiskal Jadi Nahkoda, Moneter Jadi Dayung? Perdana Wahyu Santosa Jum’at, 05 Desember 2025 – 23:55 WIB views: 759 Perdana Wahyu Santosa, Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute. Foto/Istimewa A A A Perdana Wahyu Santosa Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
Opini “Pengutamaan Fiskal?” mengangkat kegelisahan yang sah: sinyal dari pernyataan pers IMF (soal rigorous oversight atas operasi quasi-fiscal) dibaca sebagai alarm bahwa relasi fiskal–moneter Indonesia sedang bergeser—dari koordinasi sehat menjadi “fiskal dominan”. Kekhawatiran utamanya: ketika kebutuhan pembiayaan, proyek politik, dan agenda industrialisasi menekan bank sentral, independensi moneter mengendur, dan kebijakan berubah menjadi perpanjangan tangan koalisi kekuasaan.
Saya setuju pada problem dasarnya, tetapi tidak pada refleks yang sering ikut menempel: seolah solusi otomatisnya adalah kembali ke dogma “bank sentral steril, fiskal menahan diri”—versi textbook yang rapi, namun sering menutup mata pada realitas negara berkembang yang butuh investasi publik besar, punya pasar keuangan dangkal, dan kerap didera guncangan global. Tantangannya bukan memilih “fiskal atau moneter”, melainkan membedakan koordinasi yang legitimate dari dominasi yang berbahaya—dan membangun pagar institusionalnya.
Dari Koordinasi ke Dominasi Dalam krisis
koordinasi fiskal–moneter itu normal, bahkan perlu. Pandemi memberi contoh: stabilisasi likuiditas, pembelian surat utang, skema pembiayaan darurat—semuanya bisa masuk wilayah quasi-fiscal: kebijakan moneter yang efeknya mirip kebijakan fiskal, karena menanggung risiko, membagi biaya, atau memilih pemenang-sektor.
Masalah muncul ketika “darurat” menjadi kebiasaan. Fiskal dominance bukanlah sekadar “pemerintah aktif”, melainkan kondisi ketika bank sentral kehilangan kemampuan untuk mengatakan tidak karena target fiskal (defisit, biaya bunga, proyek) menjadi penentu utama arah moneter. Gejalanya biasanya macam ini:
- Instrumen sementara jadi permanen. Skema yang lahir untuk krisis tidak punya sunset clause yang tegas, tidak dievaluasi, dan berubah menjadi “alat kebijakan normal”.
- Biaya disamarkan. Kerugian/risiko dibukukan di neraca bank sentral atau lembaga lain, alih-alih transparan di APBN. Publik akhirnya “membayar” lewat inflasi, distorsi kredit, atau pelemahan disiplin anggaran—tanpa debat anggaran yang layak.
- Tujuan kebijakan kabur. Stabilitas harga, stabilitas sistem keuangan, dan agenda pertumbuhan dicampur tanpa hierarki yang jelas dan tegas. Ketika semuanya jadi tujuan, akuntabilitas menuju nol.
Di titik ini, kekuatan argumen opini tersebut tajam: relasi fiskal–moneter bukan debat teknis semata; ia debat ekonomi-politik tentang siapa yang menentukan prioritas dan siapa yang menanggung risikonya. Jika agenda industrialisasi, hilirisasi, atau proyek “nasionalisme ekonomi” dijalankan lewat kanal pembiayaan yang tidak transparan, kita berisiko memproduksi “kapitalisme koneksi” versi baru—di mana kebijakan publik menjadi subsidi terselubung bagi segelintir jaringan. Tetapi ada jebakan juga: menganggap independensi bank sentral sebagai jaminan otomatis. Bank sentral bisa independen di atas kertas namun tetap rentan “ditarik” melalui penunjukan pejabat, tekanan narasi publik, dan desain mandat yang melebar. Intinya bukan slogan “independensi”, melainkan mekanisme penolakan yang kredibel: aturan main, batas risiko, dan proses politik yang membuat pembiayaan kebijakan tidak bisa diselundupkan.
Oversight oleh Siapa, untuk Siapa? IMF secara halus tampaknya meminta rigorous oversight atas operasi quasi-fiscal. Secara teknis, itu masuk akal karena aktivitas yang efeknya fiskal harus diawasi dengan ketat. Namun di sini kritik halusnya, bahwa IMF cenderung menyukai bahasa “oversight” dan “stabilitas” sebagai solusi universal, tetapi sering mengabaikan politik dari oversight itu sendiri. Jika pengawasan hanya berarti “patuh pada indikator” (inflasi terkendali, defisit aman, neraca kuat), kita bisa tergelincir pada dua masalah: 1. Oversight jadi teater kepatuhan. Laporan rapi, tetapi pengambilan keputusan tetap tertutup dan berbasis relasi kekuasaan. 2. Stabilitas jadi fetish, sementara problem struktural (basis pajak sempit, belanja tidak produktif, ketimpangan, kapasitas industri) tidak disentuh.
Karena itu, “rigorous oversight” sebaiknya lebih diterjemahkan dan dipahami bukan sebagai “IMF mengawasi kita”, melainkan sebagai pendalaman akuntabilitas domestik: DPR/BPK/otoritas audit dan publik juga harus bisa melihat—dengan bahasa yang jelas—berapa biaya kebijakan, siapa penerimanya, apa risiko terburuknya, dan kapan kebijakan itu berakhir.
Ada resep institusional yang cukup konkret dan tidak perlu dramatis:
- Definisi resmi & daftar terbuka aktivitas quasi-fiscal (apa saja kebijakannya, lewat instrumen apa, nilainya berapa).
- Aturan “lampu lalu lintas risiko”: batas eksposur, batas kerugian, dan syarat penghentian (sunset clause) yang otomatis.
- Pelaporan fiskal risiko terpadu: semua risiko implisit (termasuk penjaminan, subsidi bunga terselubung, atau skema pembiayaan off-budget) masuk fiscal risk statement yang dibahas terbuka.
Koordinasi yang berhierarki: siapa memutus apa, dengan tujuan yang tidak saling meniadakan (stabilitas harga bukan “opsional”).
Dengan cara itu, kita tentu tidak bermaksud menolak masukan IMF— namun kita mencoba “mendaratkan” masukan itu ke tata kelola yang demokratis dan sesuai konteks problematika politik Indonesia. IMF bisa jadi cermin, tapi tidak boleh jadi pengganti akal sehat politik-ekonomi kita sendiri.
Menyelamatkan Koordinasi, Mencegah Dominasi
Opini “Pengutamaan Fiskal?” sudah tepat karena mengingatkan kita bahwa pergeseran fiskal–moneter adalah pergeseran kekuasaan, bukan sekadar pergeseran instrumen ekonomi. Namun respons yang paling berguna bukan kembali ke puritanisme moneter, melainkan membangun pagar: transparansi biaya, batas risiko, sunset clause, dan pengawasan publik yang lebih transparan dan nyata.
Di situlah Indonesia bisa punya kebijakan yang cukup lentur untuk krisis dan transformasi, tanpa menyerahkan bank sentral menjadi mesin pembiayaan politik semata. Dunia memang berantakan; justru karena itu, aturan main harus lebih jernih teratata, bukan lebih kabur.