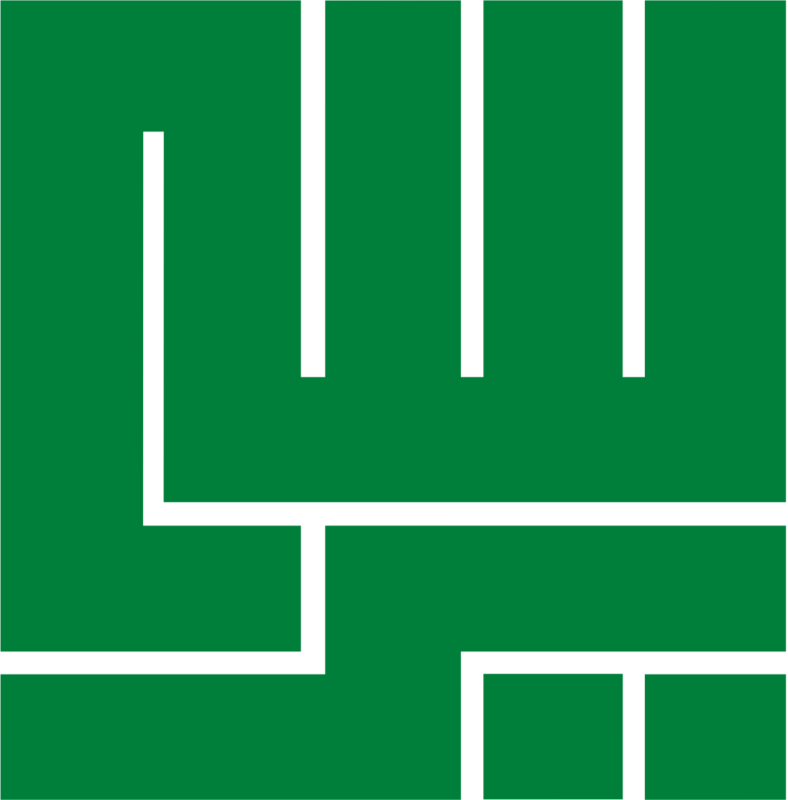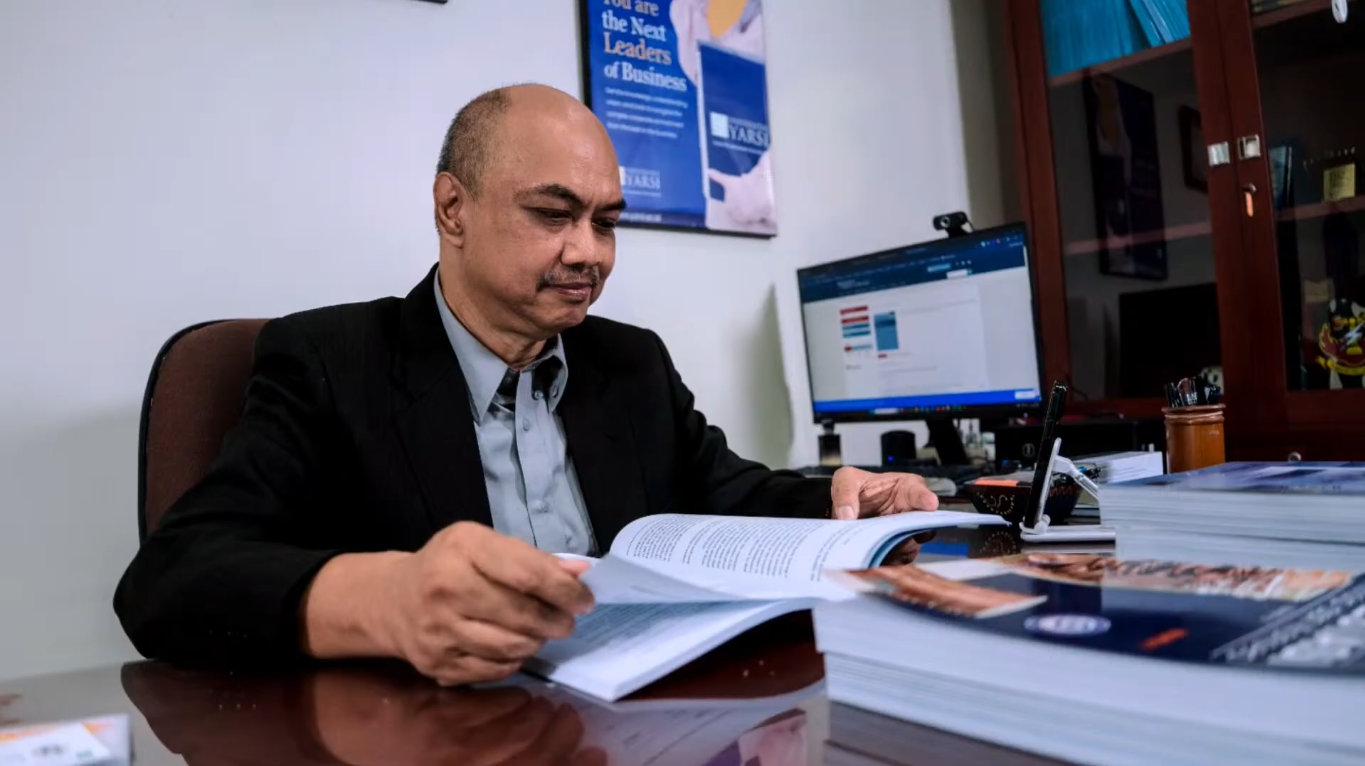Di saat ekonomi global gampang berubah mood dan konflik geopolitik yang terus meningkat—dari euforia ke cemas hanya karena suku bunga, atau harga komoditas—pemerintah butuh instrumen yang bekerja lebih cepat, terukur, dan tidak merusak fondasi. Di titik itulah, kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja tertentu (gaji tetap-teratur sampai Rp10 juta/bulan) di sektor padat karya adalah contoh “stimulus halus” yang mana tidak heboh seperti bansos besar-besaran, tetapi langsung menambah take-home pay dan menjaga ritme konsumsi.
Dari sisi target makro, Kemenkeu (dalam kerangka RAPBN 2026) menempatkan pertumbuhan pada kisaran 5,2%–5,8% (dengan sasaran resmi 5,4%)—angka yang menuntut konsumsi rumah tangga tetap kuat dan investasi tidak melemah. Kebijakan PPh 21 DTP ini, bila dieksekusi rapi, memberi bantalan psikologis dan material agar konsumsi tidak mengalami “rem kejut” ketika tekanan biaya hidup atau ketidakpastian ekonomi menaik.
Mengapa Relevan untuk Pertumbuhan?
Secara desain, PMK 10/2025 memberi insentif PPh 21 DTP untuk pegawai di industri padat karya—misalnya alas kaki, tekstil/pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit—dengan syarat pemberi kerja dan pegawai sama-sama memenuhi kriteria. Insentif berlaku atas penghasilan bruto sepanjang 2025 (Masa Pajak Januari–Desember 2025).
Kriteria pegawai inti: punya NPWP atau NIK terintegrasi, tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain, dan batas penghasilan tertentu. Untuk pegawai tetap, patokan utamanya adalah penghasilan bruto tetap-teratur tidak melebihi Rp10 juta pada Masa Pajak Januari (atau bulan pertama bekerja). Untuk pekerja tidak tetap, ada batas rata-rata Rp500 ribu per hari (atau Rp10 juta bila dibayar bulanan).
Yang sering luput adalah insentif ini bekerja sebagai “penjaga daya beli” yang sangat langsung menekankan tujuan proteksi kelas menengah-bawah, mencegah downward mobility, dan juga meredam tekanan ekonomi internal-eksternal. Secara makro, tambahan disposable income pada kelompok pekerja padat karya cenderung cepat kembali menjadi permintaan barang konsumsi dasar dinilai tepat ketika negara ingin menjaga mesin pertumbuhan tetap di atas 5%.
Risiko Fiskal, Bias Formal, dan Moral Hazard Perusahaan
Kebijakan bagus pun tetap saja punya “biaya dan jebakan”, yaitu: Pertama, ada trade-off penerimaan: PPh 21 DTP berarti negara menanggung pajak yang sebelumnya dipotong. Apabila diperpanjang tanpa kendali, tentunya bisa menekan tax ratio yang sudah kelelahan. Maka kebijakan ini harus diperlakukan sebagai stimulus terarah, lebih fokus dan bukan dijadikan kebiasaan permanen.
Kedua, bias sektor formal. Ketika pekerja informal masih sangat besar, insentif berbasis payroll otomatis lebih banyak menyentuh pekerja formal. Sehingga PMK 10/2025 mengingatkan bahwa efektivitas bisa terbatas bila mayoritas pekerja ada di informal. Kelompok ini lebih besar dari sektor formal dan terus bertumbuh. Ini penting, karena tujuan akhirnya bukan sekadar “membantu yang sudah tercatat”, tetapi mengangkat kapasitas konsumsi nasional dan memperkuat fondasi pertumbuhan.
Ketiga, risiko moral hazard: perusahaan bisa saja tergoda untuk mengatur struktur upah/kontrak agar “masuk kriteria”. Bahkan aturan PMK mengacu pada ketentuan perusahaan atau kontrak kerja untuk menentukan komponen penghasilan tetap-teratur. Maka jika tanpa pengawasan memadai, kebijakan yang niatnya proteksi bisa saja berubah menjadi arena optimasi administrasi.
Keempat, perilaku konsumsi: ada argumen bahwa kelas menengah memiliki kecenderungan menabung lebih besar dibanding kelompok miskin (MPC lebih rendah), sehingga stimulus bisa “bocor” ke tabungan. Tetapi kebocoran itu tidak otomatis buruk tentunya karena pada masa ketidakpastian, tabungan juga akan menstabilkan ekspektasi rumah tangga—yang pada akhirnya tetap menjaga konsumsi agar tidak jatuh terlalu dalam. Yang penting adalah targeting dan durasinya terukur.
Rekomendasi Strategis: Tepat Sasaran, Terukur, dan Pro-Growth
Agar kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ini secara implisit (dan nyata) membantu target pertumbuhan, saya sarankan tiga paket penguatan terukur. Pertama: monitoring berbasis data + “exit strategy” eksplisit. Paket PMK 10/2025 ini sudah menantang pertanyaan yang tepat yaitu apakah pemerintah siap monitoring dan strategi keluar? Jawabannya harus berupa indikator agar cakupan pekerja penerima, kenaikan take-home pay, perubahan konsumsi sektor ritel tertentu, dan compliance rate pelaporan SPT Masa. PMK ini menekankan pelaporan tepat waktu; lewat tenggat, insentif tidak diberikan dan pemberi kerja wajib menyetor PPh 21. Ini bisa jadi “rel pengaman” untuk disiplin administrasi.
Kedua: perketat guardrail anti-manipulasi upah. Gunakan risk-based audit untuk pola-pola anomali atau abnormalitas (misalnya lonjakan karyawan tepat di bawah Rp10 juta, atau perubahan komponen tetap-teratur yang tak selaras industri). Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi menjaga integritas kebijakan.
Ketiga: lengkapi dengan agenda formalisasi yang pro-produktivitas. Karena bias formal itu fakta, kebijakan ini sebaiknya dipasangkan dengan program yang menarik pekerja informal masuk rantai formal: insentif kepatuhan UMKM yang sederhana, upskilling yang langsung tersambung kebutuhan industri, dan penciptaan pekerjaan formal baruyang sejalan dengan penguatan sektor informal.
Penutup
PPh 21 DTP sampai Rp10 juta bukan “pajak dihapus”, melainkan stimulus terarah yang—jika diawasi ketat dan diberi batas waktu—dapat menjaga konsumsi, menahan downward mobility, dan membantu ekonomi mendekati target pertumbuhan. Tantangannya bukan pada idenya, tetapi pada disiplin eksekusi yaitu tepat sasaran, tidak dimanipulasi, dan tidak menjadi kebijakan permanen yang menggerogoti ruang fiskal yang sudah sempit. Namun sebagian ekonom juga bertanya: apa insentif untuk sektor informal agar pertumbuhan lebih kencang?
Perdana Wahyu Santosa
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute, dan CEO SAN Scientific