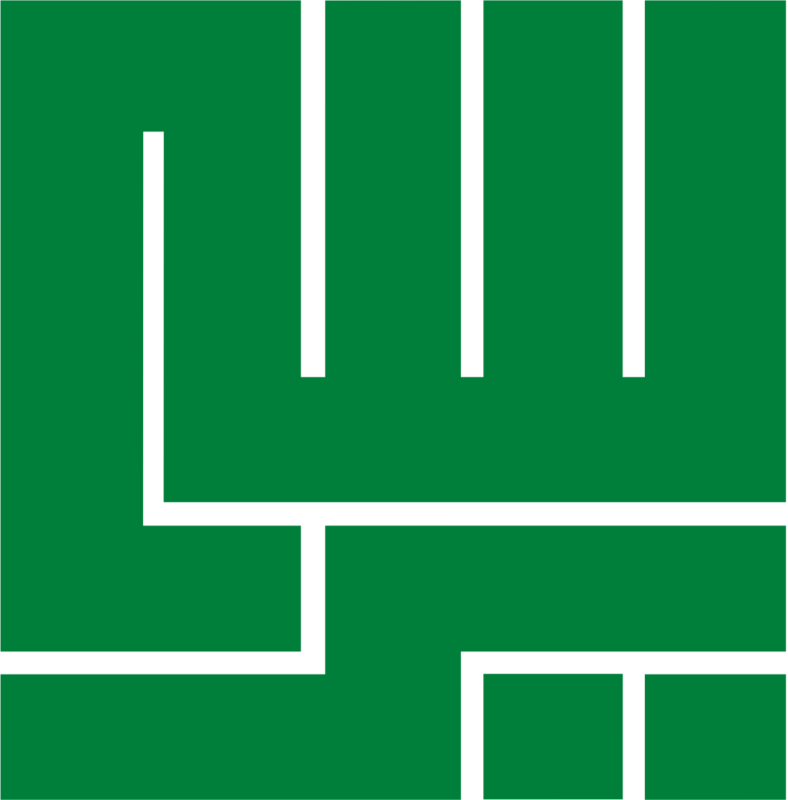Beberapa hari yang lalu, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengungkap temuan mengejutkan: 212 merek beras dari berbagai perusahaan terlibat dalam kecurangan berupa pengoplosan, pelanggaran mutu, dan ketidaksesuaian takaran kemasan. Skandal ini, yang melibatkan perusahaan besar seperti Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group), telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.
Menurut Menteri Amran, kerugian masyarakat mencapai Rp99 triliun per tahun, sementara kerugian negara, terutama akibat pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), diperkirakan Rp2 triliun per tahun atau Rp10 triliun dalam lima tahun.
Artikel ini menganalisis secara kritis akar masalah, dampak skandal ini, dan urgensi penegakan hukum serta reformasi sistemik untuk mencegah pengulangan.
Anatomi Kecurangan: Modus dan Skala Kerugian
Investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri menemukan bahwa 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu, berat kemasan, dan pelabelan. Modus kecurangan meliputi pengoplosan beras berkualitas rendah dengan beras premium, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan pengurangan takaran kemasan (misalnya, kemasan 5 kg hanya berisi 4,5 kg). Sebanyak 86% produk yang diperiksa mengklaim sebagai beras premium atau medium, padahal hanya beras biasa. Selisih harga akibat pelabelan palsu ini diperkirakan mencapai Rp2.000–Rp3.000 per kg, yang, jika dikalikan dengan volume konsumsi beras nasional (sekitar 33 juta ton per tahun), menghasilkan kerugian masyarakat hingga Rp99 triliun per tahun.
Kerugian negara sebesar Rp2 triliun per tahun terutama berasal dari penyalahgunaan beras SPHP, yang seharusnya dijual murah (sekitar Rp10.900 per kg) untuk menstabilkan harga pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, 80% beras SPHP dioplos dan dijual kembali sebagai beras premium dengan harga Rp14.000–Rp15.000 per kg, merugikan baik negara maupun konsumen. Jika praktik ini berlangsung selama lima tahun, kerugian negara mencapai Rp10 triliun, sebuah angka yang mencerminkan betapa seriusnya dampak kecurangan ini terhadap keuangan publik.
Skandal ini terdeteksi setelah Kementan mencatat anomali harga: harga gabah di tingkat petani menurun (sekitar Rp6.000 per kg), tetapi harga beras di tingkat konsumen justru naik (mencapai Rp14.000–Rp15.000 per kg). Pemeriksaan di 13 laboratorium berakreditasi di 10 provinsi penghasil beras mengonfirmasi pelanggaran pada 212 merek, dengan 26 di antaranya mengakui kecurangan setelah diperiksa Satgas Pangan Polri. Praktik ini tidak hanya terjadi di pasar tradisional, tetapi juga di supermarket dan minimarket ternama, menunjukkan betapa luasnya penetrasi kecurangan dalam rantai pasok pangan.
Akar Masalah: Kelemahan Pengawasan dan Mentalitas Bisnis
Skandal beras oplosan ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam tata kelola pangan di Indonesia, yang meliputi antara lain:
Pertama, pengawasan rantai pasok pangan yang lemah menjadi celah utama. Meskipun Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satgas Pangan Polri ada, pengawasan terhadap distribusi beras SPHP tampaknya tidak dilakukan secara konsisten. Beras SPHP, yang seharusnya diawasi ketat dari gudang Bulog hingga konsumen, mudah dioplos karena kurangnya mekanisme pelacakan dan verifikasi di tingkat distribusi.
Kedua, mentalitas bisnis yang mengutamakan keuntungan jangka pendek di kalangan pelaku usaha, termasuk perusahaan besar, memperparah masalah. Perusahaan seperti Wilmar Group dan Japfa Group, yang memiliki sumber daya besar dan reputasi nasional, seharusnya menjadi teladan dalam menjaga standar mutu. Namun, keterlibatan mereka dalam skandal ini menunjukkan kurangnya etika bisnis dan lemahnya penegakan sanksi yang memberikan efek jera.
Ketiga, koordinasi lintas instansi yang buruk juga menjadi faktor. Menteri Amran dan anggota DPR seperti Titiek Soeharto menyoroti perlunya keterlibatan aktif menteri koordinator untuk mengatasi masalah ini, menunjukkan bahwa kebijakan pangan belum dikelola secara terpadu. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan tampaknya belum diterapkan secara tegas, memungkinkan pelanggaran berulang selama bertahun-tahun.
Dampak: Krisis Kepercayaan dan Ancaman Ketahanan Pangan
Skandal ini memiliki dampak yang luas dan serius, antara lain namun tak terbatas pada:
Pertama, kerugian finansial bagi masyarakat, terutama kelompok miskin, sangat signifikan. Beras adalah kebutuhan pokok, dan kecurangan seperti ini membebani daya beli masyarakat, terutama 24,06 juta orang miskin dan 2,3 juta orang miskin ekstrem di Indonesia (data BPS 2024). Menteri Amran menyebut praktik ini “mempermainkan hajat hidup orang banyak,” terutama bagi kelompok rentan.
Kedua, kerugian negara sebesar Rp10 triliun dalam lima tahun menunjukkan bahwa program SPHP, yang dirancang untuk menjaga stabilitas harga pangan, telah disalahgunakan. Dana publik yang seharusnya membantu masyarakat justru bocor akibat praktik pengoplosan, melemahkan kepercayaan terhadap kebijakan pangan pemerintah.
Ketiga, skandal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan dan sistem pengawasan pemerintah. Anggota DPR, Daniel, mempertanyakan apakah kecurangan serupa juga terjadi pada produk pangan lain, seperti gula atau minyak goreng, mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih luas. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu kepanikan pasar dan ketidakstabilan harga beras, yang berdampak pada ketahanan pangan nasional.Keempat, petani menjadi pihak yang dirugikan karena harga gabah mereka ditekan, sementara konsumen membayar lebih untuk beras berkualitas rendah. Hal ini memperburuk ketimpangan dalam rantai pasok pangan dan melemahkan posisi petani, yang seharusnya menjadi fokus utama kebijakan pertanian.
Solusi: Penegakan Hukum Tegas dan Reformasi SistemikUntuk mengatasi skandal ini dan mencegah pengulangan, diperlukan langkah-langkah strategis yang tegas dan terkoordinasi:
Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan:
Pemerintah harus segera menerapkan sanksi berat sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengancam pelaku dengan pidana hingga 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Proses hukum terhadap 212 merek dan perusahaan yang terlibat harus dipercepat, dengan transparansi penuh melalui pengumuman daftar merek bermasalah kepada publik, seperti yang dijanjikan Menteri Amran. Sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau blacklist dari rantai pasok Bulog, juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera, terutama bagi perusahaan besar.
Peningkatan Pengawasan Rantai Pasok:
Bapanas dan Satgas Pangan harus memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok, terutama untuk beras SPHP. Teknologi pelacakan, seperti blockchain atau kode QR pada kemasan, dapat digunakan untuk memastikan beras SPHP sampai ke konsumen tanpa dioplos. Pengawasan juga harus dilakukan secara berkala, bukan hanya reaktif setelah skandal terungkap, dengan melibatkan auditor independen untuk memverifikasi mutu dan takaran di tingkat distributor dan ritel.
Koordinasi Lintas Instansi: Pemerintah perlu membentuk satuan tugas terpadu yang melibatkan Kementan, Bapanas, Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengelola kebijakan pangan secara holistik. Satgas ini harus memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi mendadak, mengevaluasi kebijakan distribusi, dan memastikan penegakan hukum yang konsisten.
Peningkatan Perlindungan Konsumen:
Pemerintah harus memperkuat implementasi UU Perlindungan Konsumen dengan membentuk badan independen untuk menangani keluhan konsumen terkait pangan. Selain itu, edukasi publik tentang cara mengenali beras berkualitas dan melaporkan kecurangan perlu digalakkan melalui kampanye media dan aplikasi daring.
Dukungan untuk Petani:
Untuk mengatasi ketimpangan dalam rantai pasok, pemerintah harus memastikan harga gabah petani tetap stabil melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang adil. Program kemitraan antara petani dan Bulog juga dapat diperluas untuk memotong peran tengkulak yang sering memanipulasi harga.
Reformasi Program SPHP:
Program SPHP harus direformasi dengan mekanisme distribusi yang lebih ketat, seperti penyaluran langsung ke kelompok masyarakat miskin melalui kartu sembako atau aplikasi digital. Hal ini akan meminimalkan peluang pengoplosan di tingkat distributor.
Peningkatan Etika Bisnis: Pemerintah dan asosiasi industri, seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), harus mendorong perusahaan pangan untuk mengadopsi kode etik yang ketat. Sertifikasi mutu wajib untuk semua merek beras yang beredar di pasar dapat menjadi langkah awal untuk memastikan kepatuhan.
Kesimpulan
Skandal kecurangan 212 perusahaan pengoplos beras mengungkap kelemahan sistemik dalam pengawasan pangan, etika bisnis, dan koordinasi kebijakan di Indonesia. Dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99 triliun per tahun dan kerugian negara Rp10 triliun dalam lima tahun, skandal ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan pangan dan kepercayaan publik.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku, baik perusahaan besar maupun kecil, menjadi langkah krusial untuk memberikan efek jera. Di samping itu, reformasi pengawasan rantai pasok, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan konsumen serta petani harus segera dilakukan. Tanpa tindakan cepat dan terpadu, skandal serupa berisiko berulang, merugikan masyarakat, dan melemahkan fondasi ketahanan pangan nasional. Masyarakat kini menunggu, apakah penegakan hukum akan benar-benar ditegakkan atau hanya menjadi janji kosong.